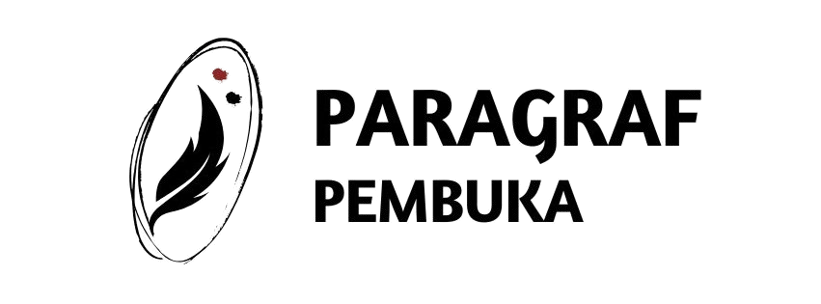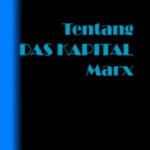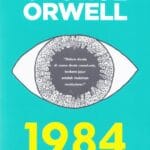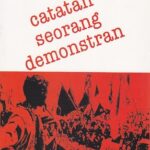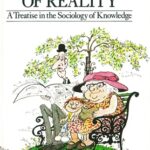Dari Hulu ke Hilir: Ekologi Rusak, Banjir pun Datang
Jakarta dan banjir, kisah lama yang terus terulang. Selama solusi hanya tambal sulam, air akan terus datang, dan kota ini akan tetap tenggelam.

|
Getting your Trinity Audio player ready... |
Jakarta dan kota-kota satelit sekitarnya kembali tenggelam pada Senin (03/03) malam. Banjir yang datang setelah hujan deras bukan lagi fenomena mengejutkan, melainkan semacam siklus tahunan yang terus berulang.
Warganya sudah seperti atlet maraton dalam menghadapi siklus ini—sigap mengevakuasi barang, membangun tanggul sementara hingga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Narasi yang kerap beredar adalah ‘banjir kiriman’ dari kawasan hulu Puncak Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Padahal, permasalahan ini bukan hanya soal volume air dari daerah yang lebih tinggi, tetapi juga soal perencanaan kota yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi ketimbang keseimbangan ekologis justru menjadi akar permasalahan ini.
Banjir bukan sekadar soal air yang tidak tahu diri, melainkan hasil dari kebijakan tata ruang yang timpang, eksploitasi lingkungan tanpa kendali, serta kurangnya kesadaran bahwa kota tidak bisa terus berkembang dengan mengorbankan ekosistem.
Pertanyaannya, sampai kapan kita terus menerapkan solusi tambal sulam tanpa benar-benar membenahi akar permasalahan?
Hulu yang Gundul, Kota yang Tak Siap
Ketika banjir melanda Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya, jari telunjuk sering kali diarahkan ke Puncak dan zona hulu lainnya: Kab. Bogor dan Kota Bogor—Katulampa masuk ke zona tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Logikanya sederhana; hujan deras mengguyur kawasan pegunungan, air meluncur deras ke bawah, dan kota di hilir pun tak kuasa menampungnya. Namun, kenyataan di lapangan lebih kompleks daripada sekadar menyalahkan hujan atau topografi.
Di hulu, hutan dan lahan hijau yang seharusnya menjadi resapan alami air hujan telah berubah menjadi deretan villa, resort, dan berbagai bentuk ekspansi komersial lainnya. Dengan semakin luasnya beton dan aspal di kawasan Puncak, air hujan kehilangan tempat untuk meresap.
Alih-alih tertahan dan terserap oleh akar-akar pepohonan, air langsung turun ke sungai dengan volume yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Sungai-sungai yang dulunya mampu menahan debit air kini justru menjadi jalur air yang meluap, membawa bencana ke daerah hilir.
Laporan investigasi dari Kompas.id mengungkap betapa maraknya praktik jual beli lahan negara berstatus Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) di kawasan Puncak. Tanah-tanah yang seharusnya masuk dalam kawasan konservasi atau hutan lindung justru diperjualbelikan dengan bebas.
Para pengembang properti, tokoh masyarakat hingga individu berkantong tebal bisa memiliki lahan di kawasan tersebut melalui makelar tanah tanpa kendala berarti. Pemerintah seolah tutup mata terhadap masifnya alih fungsi lahan yang seharusnya menjadi benteng ekologis bagi wilayah di bawahnya.
Dampaknya, kawasan yang semula berfungsi sebagai daerah resapan air di hulu Sungai Ciliwung kini dipenuhi bangunan permanen. Perizinan yang lemah, pengawasan yang longgar, dan ketidaktegasan dalam penegakan hukum lingkungan membuat kawasan hulu kian kehilangan daya serapnya.
Hasilnya? Setiap kali hujan deras turun, air tak lagi tertahan di hutan-hutan yang dulu lebat. Ia langsung mengalir deras ke hilir, membuat sungai meluap dan menyebabkan banjir yang makin sering dan makin parah.
Akan tetapi, bukan hanya kawasan hulu yang bermasalah. Di hilir, Jakarta dan kota sekitarnya sendiri juga gagal beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin berkurang, daerah resapan semakin sempit, sementara sistem drainase yang sudah uzur sering kali tidak mampu mengimbangi laju urbanisasi yang masif. Ketika air datang, ia hanya memiliki satu pilihan; menggenangi jalanan, rumah-rumah, dan pemukiman warga.
Dalam kondisi seperti ini, membangun bendungan atau normalisasi sungai mungkin terdengar seperti solusi yang masuk akal. Namun, jika akar masalahnya tidak ditangani—yakni normalisasi di hulu dan perencanaan kota yang abai terhadap daya dukung lingkungan—maka banjir hanya akan menjadi tamu tahunan yang semakin sulit diusir.
Sungai yang Tercekik dan Hilir yang Tenggelam
Dari dulu, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya hidup berdampingan dengan sungai. Ciliwung, Cisadane, Krukut, Pesanggrahan dan sungai-sungai lain yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini lebih sering disebut dalam konteks bencana.
Setiap kali hujan deras turun, bukan hanya debit air dari hulu yang menjadi masalah, tetapi juga fakta bahwa sungai-sungai ini telah kehilangan daya tampungnya.
Sebagian besar sungai di wilayah Jabodetabek tidak lagi mengalir bebas. Mereka dicekik oleh pemukiman padat yang berdiri di bantaran, sampah yang menumpuk, serta sedimentasi akibat erosi di hulu.
Sungai yang semestinya menjadi jalur alami air kini berubah menjadi kanal sempit yang berkelok-kelok melewati kota yang terus tumbuh tanpa kendali.
Dedi Ruspendi dalam “Kajian Perubahan Penutupan Lahan pada DAS Ciliwung Hulu dengan Pendekatan Spasial Dinamik” menyatakan bahwa luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang seharusnya menjadi area resapan air justru semakin menyusut. Alih fungsi lahan untuk permukiman dan infrastruktur menyebabkan sungai kehilangan daerah limpahannya.
Diperparah lagi dengan fakta bahwa lebih dari 95 persen permukaan tanah di Jakarta telah tertutup beton dan aspal, yang membuat air hujan tidak memiliki ruang untuk meresap.
Hasilnya, setiap kali hujan turun, air langsung mengalir ke sungai yang sudah menyempit dan dangkal. Tidak butuh waktu lama sebelum sungai meluap dan menggenangi kota.
Permasalahannya tidak berhenti di situ. Sungai yang tercekik ini juga berhadapan dengan realitas bahwa hilirnya tidak siap menampung luapan air.
Jakarta, sebagai kota dengan banyak kawasan rendah, sangat bergantung pada sistem pompa dan drainase buatan untuk mengalirkan air ke laut. Sayangnya, sistem ini sering kali kalah cepat dibandingkan laju air yang datang dari hulu dan limpasan air hujan lokal.
Tanggul-tanggul yang dibangun untuk menahan air laut masuk juga memiliki tantangannya sendiri. Beberapa di antaranya sudah tua dan rentan jebol, sementara permukaan tanah di Jakarta terus mengalami penurunan.
Kombinasi antara rob dan banjir dari darat menciptakan skenario di mana beberapa wilayah benar-benar berada dalam kondisi terjepit; air dari sungai tidak bisa mengalir keluar, sementara air dari laut siap masuk kapan saja.
Dalam situasi ini, pembenahan sungai tidak bisa hanya dilakukan dengan pengerukan sesekali atau proyek normalisasi yang setengah hati. Perlu ada perubahan fundamental dalam cara kota berhubungan dengan sungainya.
Program restorasi sungai yang mencakup pelebaran kembali daerah aliran sungai, relokasi pemukiman di bantaran, serta pengendalian erosi di hulu, harus menjadi prioritas.
Lebih dari itu, masyarakat juga harus diajak untuk melihat sungai bukan hanya sebagai saluran air atau tempat membuang sampah, tetapi sebagai bagian dari ekosistem kota yang harus dijaga. Sebab, tanpa sungai yang sehat, Jakarta dan kota-kota lain di hilir hanya akan terus mengulang siklus yang sama: hujan deras, sungai meluap, dan banjir yang tak kunjung usai.
Menata Ekologi, Bukan Sekadar Infrastruktur
Menanggulangi banjir di kota sebesar Jakarta bukan sekadar persoalan menambah pompa, meninggikan tanggul, atau memperlebar sungai. Sebab, akar masalahnya lebih dalam dari sekadar infrastruktur.
Selama ekologi dikesampingkan dan solusi yang diambil hanya berfokus pada pembangunan fisik, banjir akan tetap datang seperti tamu tak diundang setiap musim hujan.
Pendekatan ekologis harus menjadi arus utama dalam penanganan banjir, bukan hanya pelengkap kebijakan yang sekadar terlihat progresif di atas kertas. Salah satu langkah mendesak adalah menghentikan alih fungsi lahan di kawasan hulu, khususnya di Puncak dan daerah resapan air lainnya.
Sudah terlalu banyak ruang hijau yang dikorbankan demi villa, resort, dan properti komersial, seolah-olah lahan di sana tidak punya fungsi lain selain investasi. Pemerintah harus memperketat regulasi, menindak tegas makelar tanah, dan merehabilitasi kawasan yang sudah telanjur rusak.
Di hilir, sistem drainase alami perlu dipulihkan. Saat ini, air hujan yang jatuh di Jakarta tidak memiliki cukup ruang untuk meresap karena tanahnya sudah diselimuti beton. Alih-alih menumpuk proyek betonisasi, kebijakan tata kota harus lebih berpihak pada solusi berbasis alam, seperti memperbanyak ruang terbuka hijau yang benar-benar berfungsi sebagai daerah resapan, bukan sekadar taman estetis.
Penerapan konsep kota spons—yang memungkinkan air terserap ke dalam tanah sebelum mengalir ke sungai—harus dipertimbangkan secara serius.
Sungai yang semakin sempit dan dangkal juga perlu direstorasi secara menyeluruh. Namun, ini bukan hanya soal pengerukan atau normalisasi. Pendekatan naturalisasi yang mengedepankan keseimbangan antara ekosistem sungai dan kebutuhan kota bisa menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.
Jika sungai diperlakukan hanya sebagai saluran pembuangan air tanpa memperhitungkan keberlanjutan ekosistemnya, setiap penyesuaian infrastruktur yang dilakukan hanya akan bersifat sementara.
Jakarta dan kota satelit sekitarnya juga harus berani berinvestasi pada sistem peringatan dini dan mekanisme respons bencana yang lebih baik. Kota ini bukan baru sekali atau dua kali kebanjiran, tapi hampir setiap tahun mengalami skenario serupa. Kesigapan pemerintah dalam memitigasi dampak banjir harus lebih dari sekadar rutinitas tahunan.
Mengatasi banjir di Jakarta memang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Namun, selama pendekatan yang diambil masih berkutat di seputar proyek infrastruktur tanpa menyentuh akar masalah ekologis, setiap musim hujan hanya akan membawa siklus yang sama: hujan turun, air meluap, warga kebanjiran, pemerintah panik, lalu solusi instan kembali dijadikan andalan.
Jika ingin perubahan nyata, cara berpikir dan bertindak harus bergeser dari reaktif menjadi preventif—dari membangun lebih banyak beton menjadi merawat ekosistem yang sudah ada.